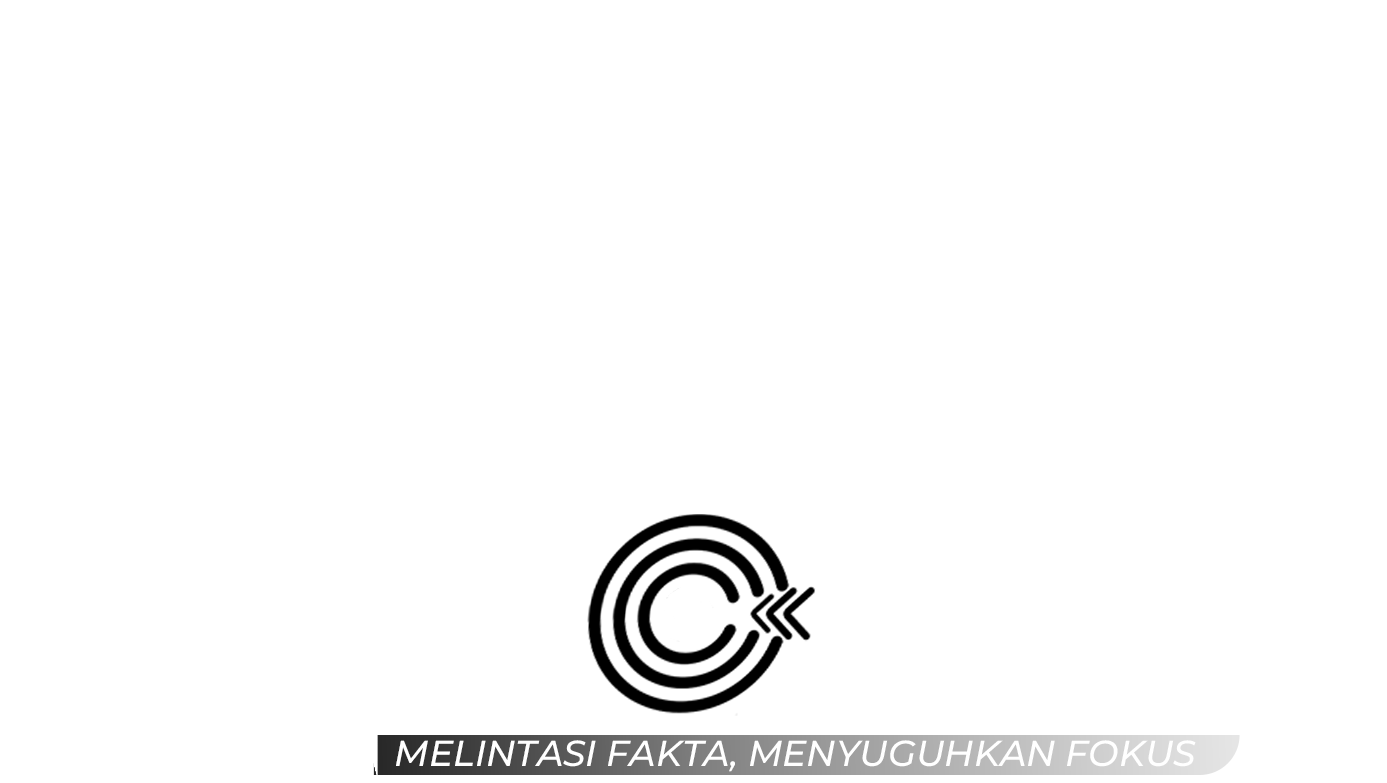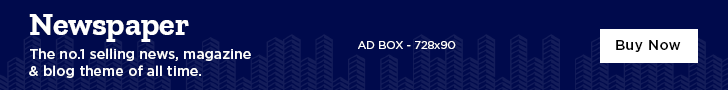Lintas Fokus – Pada 10 November 2025, ketika layar televisi menyorot ruang upacara di Istana Negara, nama Soeharto kembali menggema ke seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden yang memimpin selama tiga dekade itu, dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Di saat yang sama, di luar istana dan di berbagai kota, spanduk penolakan dan unjuk rasa bermunculan menandai betapa terbelahnya memori kolektif bangsa terhadap sosok ini.
Dalam upacara yang dihadiri keluarga penerima gelar, Prabowo menyerahkan plakat dan Keppres kepada Siti Hardijanti Rukmana, putri Soeharto. Kamera menangkap momen keduanya berjabat tangan di depan potret besar sang mantan presiden. Bagi pendukung, inilah momen penebusan, ketika negara akhirnya mengakui secara resmi jasa militer dan pembangunan di era Orde Baru. Bagi penentang, adegan itu terasa seperti penghapus pelan terhadap jejak pelanggaran HAM dan represivitas yang selama ini mereka suarakan.
Keputusan ini tidak datang secara mendadak. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, sudah menyampaikan bahwa Soeharto memenuhi syarat administratif dan historis untuk diajukan sebagai Pahlawan Nasional. Dewan Gelar lalu merekomendasikan namanya bersama sembilan tokoh lain yang kemudian ditetapkan lewat Keppres.
Namun begitu Presiden mengumumkannya, pro dan kontra tak terbendung. Di media sosial, nama Soeharto langsung menempati posisi teratas trending topic. Di berbagai pemberitaan internasional, mulai dari Reuters, Financial Times, hingga The Guardian, Indonesia digambarkan sedang “mengangkat kembali” seorang penguasa yang di banyak negara dilabeli sebagai diktator, kali ini dengan cap Pahlawan Nasional yang diberikan oleh menantunya sendiri.
Latar Sejarah dan Alasan Pemberian Gelar
Bagi pendukung, titik berangkatnya jelas. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak 1967 hingga dipaksa turun pada 1998, setelah krisis moneter Asia dan demonstrasi besar-besaran. Sebelum menjadi presiden, ia adalah perwira militer yang terlibat dalam berbagai operasi penting sejak masa revolusi, termasuk peran militer dalam konflik Irian Barat.
Pemerintah menonjolkan beberapa hal ketika mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Pertama, kontribusinya dalam penataan ulang angkatan bersenjata setelah kemerdekaan dan keterlibatannya dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Kedua, program pembangunan ekonomi Orde Baru yang dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan, menggenjot produksi pangan lewat “revolusi hijau”, dan memperluas infrastruktur hingga pelosok. Narasi “Bapak Pembangunan” yang lama melekat di masa Orde Baru kembali muncul di ruang publik saat gelar Pahlawan Nasional ini diumumkan.
Dalam wawancara dan pernyataannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa Dewan Gelar bekerja dengan kriteria yang berlaku bagi semua tokoh, mulai dari integritas, pengabdian, hingga dampak perjuangan bagi negara. Ia menolak pandangan bahwa pemberian gelar untuk Soeharto adalah bentuk “pencucian sejarah”, dan menyebut sejarah harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi gelapnya.
Di atas kertas, keputusan Presiden juga didukung fakta bahwa partai-partai besar yang memiliki akar sejarah kuat dengan Orde Baru, terutama Golkar, masih memiliki basis politik yang signifikan di parlemen dan di daerah. Dukungan politik inilah yang membuat jalan formalisasi gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menjadi mungkin, setelah bertahun-tahun usulan serupa kandas di tengah perdebatan.
Argumen Pendukung dan Narasi Prestasi Orde Baru
Kelompok yang mendukung gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto biasanya menggarisbawahi tiga hal besar. Pertama, stabilitas politik. Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia relatif bebas dari konflik politik terbuka berskala besar di tingkat pusat. Di mata mereka, stabilitas ini memberi ruang bagi pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan di banyak daerah.
Kedua, capaian ekonomi. Di masa Soeharto, Indonesia bertransformasi dari negara dengan ekonomi pertanian miskin menjadi negara dengan struktur ekonomi yang lebih beragam. Berbagai laporan internasional mencatat adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tertentu, sekaligus ekspansi infrastruktur, listrik, dan pendidikan dasar. Meski angka persis sering diperdebatkan, pendukung memandang bahwa tanpa fondasi Orde Baru, Indonesia tidak akan bisa tumbuh seperti sekarang.
Ketiga, posisi geopolitik. Dalam logika Perang Dingin, Soeharto dipandang sebagai pemimpin yang mampu menjaga Indonesia tetap berada di jalur anti-komunis, namun tetap memainkan peran penting dalam Gerakan Non Blok. Dukungan Barat terhadap pemerintahannya kala itu sering dijadikan bukti bahwa ia dianggap mampu menjaga stabilitas kawasan dan membuka pintu investasi.
Bagi sebagian masyarakat, terutama generasi yang tumbuh di era Orde Baru, nama Soeharto identik dengan harga-harga yang dianggap relatif terkendali, program transmigrasi, serta pembangunan jalan dan irigasi yang konkret terasa. Di media sosial, tak sedikit yang menulis komentar bernuansa nostalgia, membandingkan kondisi ekonomi dan keamanan dulu dan sekarang untuk membenarkan gelar Pahlawan Nasional ini.
Namun di seberang narasi keberhasilan ekonomi dan stabilitas ini, berdiri barisan kritik yang menolak keras pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan.
Soeharto dalam Kaca Mata Korban dan Aktivis HAM
Aktivis HAM, akademisi, dan keluarga korban kekerasan politik 1965 langsung menyebut keputusan memberi gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto sebagai bentuk “rewriting history”. Mereka mengingatkan bahwa naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari pembantaian massal 1965–1966, ketika ratusan ribu orang diduga tewas dalam gelombang pembunuhan anti-komunis, serta penahanan dan penyiksaan terhadap mereka yang dituduh terlibat.
Media seperti The Guardian dan Financial Times mencatat bagaimana Amnesty International dan kelompok HAM lokal mengecam langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Mereka menilai gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mengabaikan korban pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, Papua, dan berbagi peristiwa kekerasan politik lainnya di era Orde Baru.
Organisasi seperti KontraS mengingatkan kembali rekam jejak pelanggaran HAM yang pernah didokumentasikan, mulai dari praktik penahanan tanpa pengadilan, penghilangan paksa aktivis, hingga pembungkaman media dan oposisi politik. Tempo merangkum berbagai kasus yang pernah dilekatkan pada rezim Soeharto, termasuk dugaan keterlibatan dalam operasi militer di Timor Timur dan kekerasan menjelang jatuhnya Orde Baru.
Sejarawan UGM yang diwawancarai oleh NU Online menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berpotensi menutupi atau minimal mengaburkan penilaian kritis terhadap pelanggaran di masa pemerintahannya. Menurut mereka, ketika negara memberi stempel “pahlawan”, publik cenderung melihat sisi heroik dan melupakan sisi gelap, kecuali jika pendidikan sejarah di sekolah secara serius mengajarkan dua sisi itu sekaligus.
Di jalanan, aksi protes digelar oleh kelompok pro demokrasi dan keluarga korban Orde Baru. Di Jakarta, demonstran membawa poster berisi wajah Soeharto berdampingan dengan tulisan “jangan lupakan korban”. Aksi Kamisan dan kelompok korban 1998 menyebut keputusan ini sebagai “tamparan” bagi perjuangan panjang menuntut keadilan yang sampai hari ini belum selesai
Wajib Tahu:
Laporan-laporan investigatif menyebut bahwa di masa kekuasaan Soeharto mengalir tuduhan korupsi hingga puluhan miliar dolar AS dan berbagai pelanggaran HAM berat, tetapi ia tidak pernah diadili di pengadilan pidana sebelum wafat pada 2008, dengan alasan kesehatan.
Dampak Politik Penetapan Pahlawan Nasional
Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah: apa arti pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bagi arah demokrasi Indonesia?
Di level simbolik, langkah ini dibaca oleh banyak pengamat sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah Prabowo ingin menata ulang narasi sejarah resmi negara, menempatkan Orde Baru lebih sebagai periode stabilitas dan pembangunan, bukan rezim represif. Posisi Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang mengurusi penulisan sejarah resmi menambah kekhawatiran bahwa kurikulum dan narasi publik ke depan akan makin “ramah” terhadap Orde Baru.
Di sisi lain, bagi kelompok yang merindukan stabilitas dan ketertiban ala Orde Baru, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto memperkuat legitimasi nostalgia itu. Mereka merasa pandangan mereka terhadap masa lalu kini mendapatkan segel dari negara, dan tidak hanya hidup di ruang obrolan keluarga atau grup WhatsApp.
Secara politik praktis, keputusan ini juga mempertebal kedekatan simbolik antara Prabowo dan Soeharto, bukan hanya sebagai mantan menantu, tetapi sebagai pewaris sebagian agenda politik dan basis sosial Orde Baru. Sejumlah analis memperingatkan risiko kemunduran demokrasi jika penghormatan terhadap figur otoritarian tidak diimbangi penguatan serius terhadap lembaga-lembaga pengawasan, kebebasan pers, dan perlindungan hak sipil.
Di tengah semua itu, publik berada di persimpangan. Satu sisi diminta menghormati keputusan negara yang mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, sisi lain mengingatkan bahwa menghormati bukan berarti melupakan atau menghapus jejak kejahatan yang pernah dicatat. Masa depan perdebatan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah, media, seniman, peneliti, dan keluarga korban terus menghidupkan fakta dan diskusi terbuka tentang sejarah Orde Baru.
Satu hal yang pasti: dengan gelar Pahlawan Nasional yang kini resmi disematkan, nama Soeharto tidak akan tenggelam begitu saja. Ia justru akan makin sering diperdebatkan, dipertanyakan, dan ditafsir ulang, menjadi cermin sejauh mana Indonesia berani jujur terhadap masa lalunya sendiri.
Sumber: The Guardian