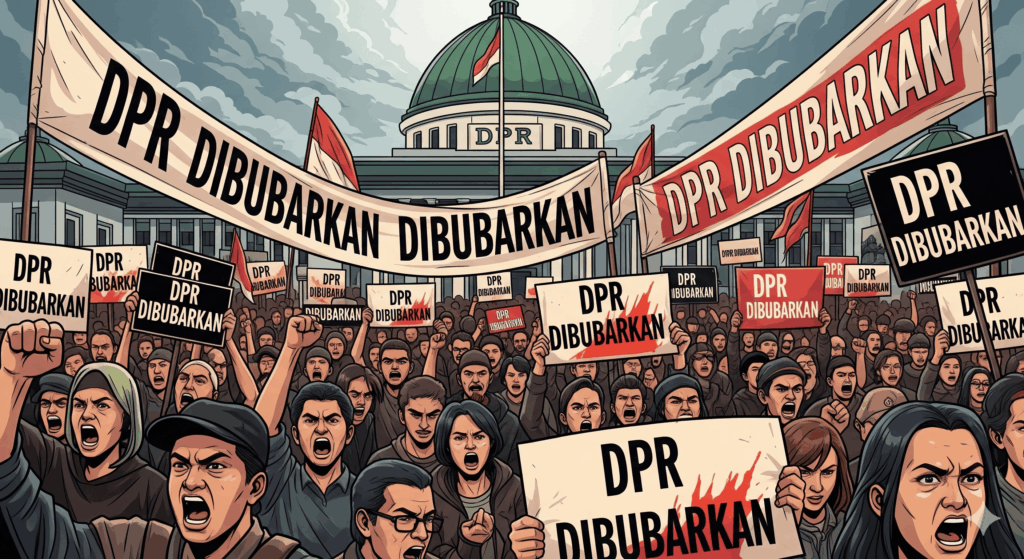Lintas Fokus – Di tengah derasnya amarah jalanan beberapa hari terakhir, satu slogan melesat di poster dan lini masa: DPR dibubarkan. Emosinya mudah dipahami—publik murka melihat respons negara yang dianggap lambat mengusut kekerasan saat demo, hingga gelombang aksi yang terus meluas dan menyasar simbol-simbol kekuasaan. Tetapi ada pertanyaan yang wajib dijawab dengan kepala dingin: secara hukum, apakah “DPR dibubarkan” itu mungkin dilakukan? Dalam desain ketatanegaraan pascareformasi, jawabannya tidak—setidaknya tidak dengan cara cepat atau lewat dekret satu pihak. Konstitusi kita sengaja dirancang untuk mencegah itu. Di saat yang sama, tuntutan perubahan tetap sah dan mendesak; hanya saja jalannya harus konstitusional agar hasilnya kuat, tidak kontraproduktif, dan tidak menjerumuskan negara ke krisis baru. Untuk konteks, eskalasi aksi memang meningkat setelah tewasnya seorang pengemudi ojol di sekitar parlemen; koalisi mahasiswa pun berikrar melanjutkan demonstrasi dan menargetkan institusi kepolisian sebagai sasaran protes berikutnya.
Fakta Konstitusi: Presiden Tak Punya Tombol “Bubarkan DPR”
Sejak Perubahan Ketiga UUD 1945, aturan mainnya jelas: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” (Pasal 7C). Larangan eksplisit ini adalah pagar agar pengalaman kelam masa lalu tidak berulang. Dengan kata lain, seruan DPR dibubarkan via dekret presiden bertentangan langsung dengan teks UUD. Ketentuan prosedur perubahan UUD sendiri berada di Pasal 37—usul minimal 1/3 anggota MPR, rapat perubahan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, dan keputusan diambil sesuai syarat ketat pasal tersebut. Tidak ada jalan pintas di luar rambu ini.
Di luar itu, perlu diluruskan satu miskonsepsi yang kerap muncul saat wacana DPR dibubarkan memanas: Indonesia tidak memiliki mekanisme referendum dalam kerangka hukum mutakhir. UU Referendum 1985 sudah dicabut oleh UU 6/1999, sehingga gagasan “tanya rakyat langsung lewat referendum untuk bubarkan DPR” tidak punya dasar hukum. Jika suatu saat Indonesia ingin menghidupkan kembali referendum, ia harus lebih dulu diatur melalui produk perundang-undangan baru dan/atau perubahan UUD yang sah.
Wajib Tahu:
Pasal 7C UUD 1945 melarang presiden membekukan/membubarkan DPR; Pasal 37 mensyaratkan kuorum 2/3 untuk mengubah UUD; UU 6/1999 mencabut UU Referendum 1985—tak ada referendum dalam skema saat ini.
Apakah DPR dibubarkan Mungkin Secara Hukum?
Secara positif hukum saat ini, tidak. Satu-satunya pintu untuk mewacanakan “riset ulang parlemen” adalah amandemen UUD melalui mekanisme Pasal 37 di MPR. MPR sendiri—pascaamandemen—tidak diberi “palunya” untuk membubarkan DPR secara rutin; kewenangannya terbatas pada yang diatur UUD (misalnya menetapkan/mengubah UUD, melantik presiden, memutus pemberhentian presiden sesuai koridor konstitusi). Mengambil rute di luar Pasal 37 berarti mengundang krisis ketatanegaraan. Karena itu, menuntut DPR dibubarkan tanpa rencana amandemen yang legitimate sama dengan memaksa sistem berjalan di luar rel. Sementara itu, gelombang aksi hari-hari ini—yang didorong isu akuntabilitas aparat dan kesejahteraan—tetap sah disalurkan; namun targetnya sebaiknya diarahkan ke reformasi kebijakan dan kelembagaan yang bisa dieksekusi sekarang, bukan ke slogan yang secara hukum buntu.
Opsi Reformasi yang Sah: Kontrol Parlemen, PAW, & Uji Materi
Alih-alih menabrak tembok hukum dengan teriakan DPR dibubarkan, ada sejumlah jalan reformasi yang lebih cepat terasa sekaligus konstitusional:
1) Maksimalkan hak pengawasan DPR. Gunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk menguliti kebijakan yang dipersoalkan publik—dari tata kelola pengamanan aksi sampai belanja dan privilese pejabat. Mekanisme ini sudah tersedia di UUD 1945/UU MD3; tekanan publik seharusnya didorong agar fraksi-fraksi benar-benar mengaktifkannya, bukan sekadar menyebutnya di konferensi pers.
2) Koreksi personal lewat PAW/“recall”. Bila ada anggota yang gagal memenuhi mandat etis/kerja, Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah instrumen yang sah. Isu “hak recall parpol” bahkan baru diuji di Mahkamah Konstitusi tahun 2025, dan MK menolak permohonan—artinya desain hukum recall/PAW dalam UU MD3 masih berlaku, dengan segala syaratnya. Dorong partai untuk memakainya secara bertanggung jawab, serta awasi prosesnya.
3) Gugat kebijakan, bukan negara. Banyak keberatan demonstran sejatinya objek uji di pengadilan: uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi (jika bertentangan dengan UUD) atau uji peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung. Jalur ini sering “dingin” tetapi berbuah konkret: pasal/aturan yang inkonstitusional dapat dipangkas tanpa kegaduhan “DPR dibubarkan”.
4) Jika tetap ingin “reset” sistem, tempuh amandemen. Publik dan elite dapat merumuskan amandemen terarah—misalnya membuka opsi pemilu sela atau pembubaran parlemen terkondisi—tetapi hanya via Pasal 37 (usul 1/3 anggota MPR, kuorum 2/3 hadir, dan putusan sesuai ketentuan). Ini sulit, tetapi inilah pagar demokrasi agar perubahan fundamental tidak merusak fondasi negara hukum.
Solusi 30 Hari untuk Meredakan Demo: Dari Parlemen Terbuka ke Akuntabilitas Aparat
Pemerintah dan DPR jangan defensif; publik butuh jadwal kerja, bukan jargon. Agar energi jalanan tidak terperangkap di seruan DPR dibubarkan, berikut paket langkah yang jelas target dan tenggatnya:
-
RDPU/RDP on-site dan disiarkan publik: undang mahasiswa, serikat buruh, komunitas ojol, dan lembaga HAM. Keluarkan matriks tindak lanjut—apa yang diubah, siapa penanggung jawab, kapan tenggat—agar publik bisa memantau progres, bukan janji.
-
Aktifkan hak angket atas dugaan ekses kekerasan aparat saat demo; susun daftar pertanyaan, saksi ahli, serta timeline sidang yang transparan.
-
Rencana legislasi pro-kesejahteraan: prioritaskan revisi aturan yang menekan upah/jaminan sosial; rilis policy brief mingguan yang bisa diaudit publik.
-
Akuntabilitas aparat berbasis bukti: publikasikan tahapan penyelidikan atas kasus tewasnya pengemudi ojol di sekitar DPR—status tersangka, pasal yang dikenakan, perkembangan berkas. Ini bukan sekadar empati, tapi uji kredibilitas institusi keamanan. Eskalasi aksi yang menghantam pasar dan rupiah hari ini menunjukkan bahwa ketidakpastian politik berbiaya ekonomi; transparansi proses hukum membantu memulihkan kepercayaan.
-
Dashboard informasi demo real-time: data rekayasa lalu lintas, penangkapan, dan layanan publik selama aksi—agar hoaks tidak mengisi kekosongan informasi.
Jika paket di atas dijalankan serius dalam 30 hari, kita tidak butuh slogan DPR dibubarkan untuk melihat perubahan terasa. Demokrasi yang matang bergerak dengan instrumen yang sah, sehingga hasilnya tahan uji—di pengadilan maupun di memori publik.
Sumber: IDN Times