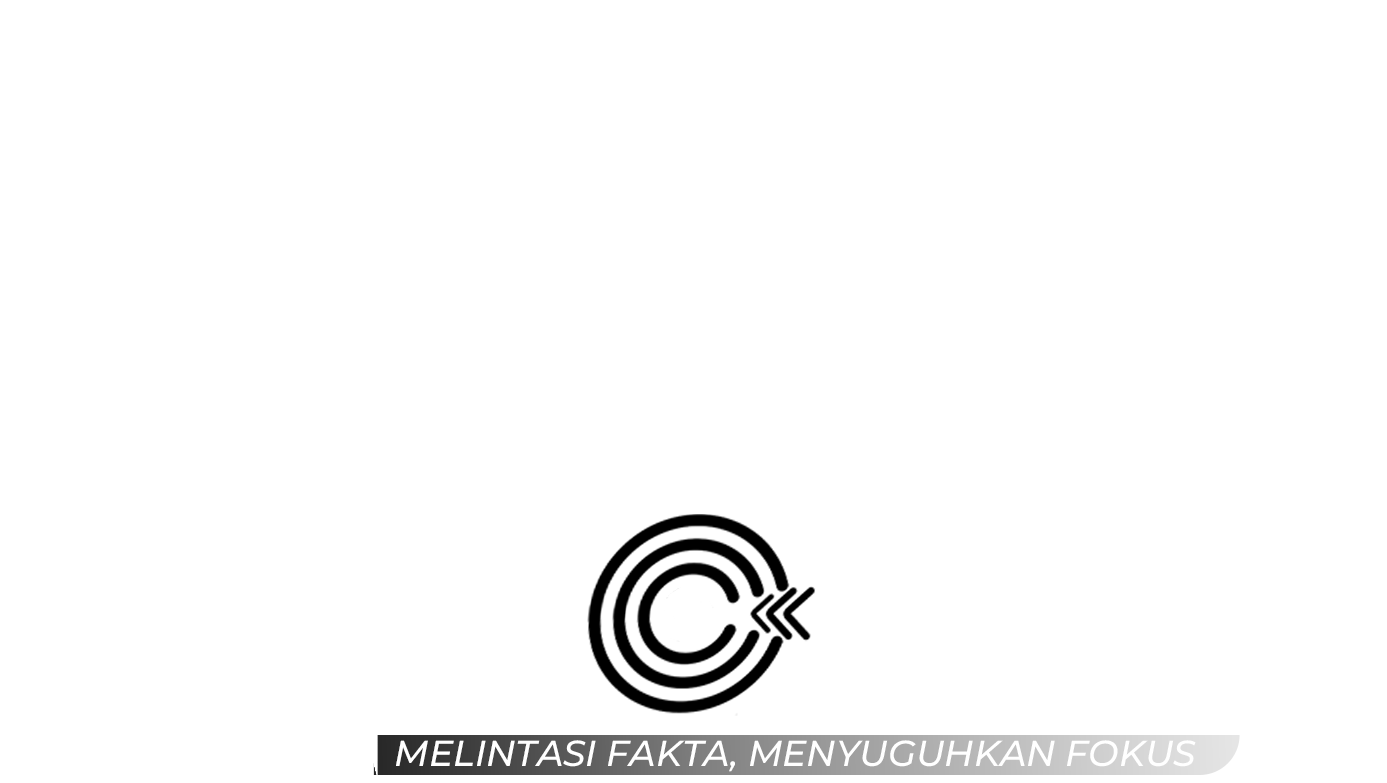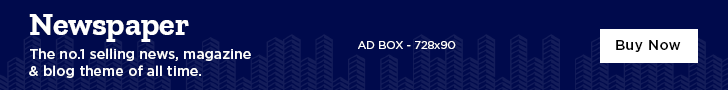Lintas Fokus – Isu Royalti Musik kembali jadi bahan obrolan dari lini masa sampai meja kasir. Ada yang mengira pelanggan akan ditagih per lagu, ada pula yang buru-buru mematikan musik di toko karena takut “kena” biaya. Pemerintah menegaskan garis besarnya: Royalti Musik tidak dikenakan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi kewajiban pemilik tempat/penyelenggara saat ada penggunaan komersial. Dengan penegasan ini, publik tak perlu waswas tiap kali mendengar lagu di kafe atau mal; yang perlu ditata adalah perizinan dan pelaporan di sisi pelaku usaha serta tata kelola lembaga pengumpul royalti.
Dalam beberapa pekan terakhir, regulasi turunan juga diperbarui. Permenkumham No. 27 Tahun 2025 hadir sebagai pelaksana teknis PP 56/2021, mempertegas bahwa pungutan Royalti Musik dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pemerintah, DJKI, dan para Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) mendorong digitalisasi pelaporan agar arus uang dari pengguna ke pemegang hak lebih transparan dan mudah diaudit. Di atas kertas, ini langkah maju. Namun, seperti biasa, iblisnya ada di detail: definisi “komersial”, metode penetapan tarif, dan distribusi royalti ke pencipta sering kali memicu debat—dan itulah yang kembali menghangat sekarang.
Apa Sebenarnya yang Diatur
PP 56/2021 meletakkan fondasi: setiap penggunaan lagu/musik secara komersial—artinya dipakai untuk memperoleh keuntungan atau menunjang kegiatan usaha—memerlukan lisensi, dan royalti atas penggunaan itu dihimpun secara kolektif. Permenkumham 27/2025 melengkapi detailnya: kanal pembayaran, jenis usaha yang wajib berlisensi, sampai tata cara pelaporan kepada LMKN. Dalam praktik, “komersial” bukan berarti pesta ulang tahun di rumah atau mendengarkan musik pribadi. Yang dimaksud adalah pemutaran di ruang publik/berbayar—hotel, restoran, kafe, pusat hiburan, penyiaran, hingga layanan digital tertentu—yang menjadikan musik sebagai daya tarik atau penopang bisnis.
Di titik ini, banyak kesalahpahaman lahir dari minimnya sosialisasi. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyamakan Royalti Musik dengan pajak. Padahal, ini bukan pajak negara; ini imbalan kepada pencipta/pemilik hak cipta atas pemanfaatan karya mereka. Pemerintah juga sudah meluruskan isu yang beredar: lagu kebangsaan “Indonesia Raya” berstatus domain publik sehingga tidak dipungut royalti selama digunakan sesuai ketentuan. Klarifikasi semacam ini penting agar pelaksanaan di lapangan tidak berubah menjadi operasi “tagih apa saja”.
Royalti Musik: Siapa Bayar dan Bagaimana Tarifnya
Sederhana: yang membayar adalah pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial. Itu bisa penyelenggara acara berbayar, promotor, pengelola hotel/restoran/kafe, tempat karaoke, stasiun radio/TV, hingga platform yang menyediakan musik untuk layanan komersial. Royalti Musik disetor ke LMKN melalui skema lisensi kolektif, lalu LMKN/LMK mendistribusikannya ke pencipta, pemilik hak terkait, dan pihak yang berhak lainnya.
Bagaimana penetapan tarif? Regulasi menyebut sejumlah parameter objektif: kategori usaha, luas area, kapasitas tempat duduk, tingkat okupansi/omzet, frekuensi pemutaran, hingga tingkat keterpaparan musik dalam pengalaman konsumen. Artinya, kafe 30 kursi di kota kecil tidak seharusnya disamakan dengan arena konser atau jaringan hotel bintang lima. Di ranah acara privat yang “dijual sebagai paket” (misalnya pernikahan komersial dengan EO, panggung, tiket/sponsorship), beberapa LMK memberi acuan persentase biaya produksi sebagai basis perhitungan. Di sinilah pelaku usaha meminta metodologi yang jelas dan dapat ditelusuri, agar Royalti Musik terasa wajar, bukan menakutkan.
Pelajaran dari negara lain tegas: tarif yang adil lahir dari data. Karena itu, pemerintah mendorong dashboard digital untuk aplikasi lisensi, unggah bukti penggunaan, dan pelaporan set list. Jika pelaporan berjalan, sengketa dapat dipangkas dan distribusi ke musisi jadi lebih tepat sasaran.
Mengapa Polemik Terus Muncul
Pertama, definisi “komersial” sering multitafsir. Ada yang menganggap pesta keluarga di gedung hotel otomatis komersial, ada yang beranggapan semua resepsi tanpa tiket adalah nonkomersial. Ruang abu-abu ini menimbulkan ketegangan di lapangan. Kedua, ketidakseragaman sosialisasi. Di satu daerah, pelaku usaha sudah paham prosedur; di daerah lain, beredar surat penagihan yang membuat kaget pemilik usaha kecil. Ketiga, transparansi distribusi. Musisi ingin melihat siapa membayar berapa, diputar di mana, dan berapa yang mereka terima. Tanpa laporan granular lintas LMK, kecurigaan mudah tumbuh. Keempat, keterlibatan asosiasi. PHRI, pelaku ritel, hingga komunitas event organizer mendorong ruang dialog yang nyata—bukan hanya sosialisasi satu arah—agar Royalti Musik bisa diterapkan tanpa “mencekik” arus kas usaha.
Polemik juga kerap dipicu oleh rumor. Misalnya, kabar bahwa Royalti Musik dibebankan langsung ke pelanggan per lagu atau per menit. Pemerintah sudah menampik narasi ini. Jika restoran mengubah strategi harga, itu kebijakan bisnis masing-masing, bukan mandat regulasi. Intinya, Royalti Musik tetap kewajiban pihak yang memutar karya untuk menunjang bisnisnya—bukan kewajiban orang yang sekadar makan bakso sambil mendengar lagu.
Langkah Praktis Agar Usaha, Musisi, dan Publik Sama-Sama Aman
Pertama, urus lisensi. Pelaku usaha sebaiknya mendaftar ke LMKN/LMK yang relevan, memahami kategori usahanya, dan mengisi data tempat/kapasitas agar tarifnya sesuai fakta, bukan perkiraan. Kedua, rapikan playlist. Gunakan sumber legal; catat lagu yang diputar untuk memudahkan pelaporan. Ketiga, arsipkan bukti. Simpan kontrak, bukti setoran, dan korespondensi agar sengketa tidak melebar. Keempat, minta rincian distribusi dari LMK/LMKN. Semakin rinci laporan yang tersedia, semakin besar kepercayaan ekosistem. Kelima, ikutkan asosiasi. Suara kolektif—PHRI, asosiasi ritel, promotor—membantu menyeragamkan pemahaman dan menegosiasikan parameter tarif yang proporsional.
Dari sisi pemerintah dan lembaga pengelola, dua hal krusial perlu dikawal. Pertama, satu sumber data yang bersih: pusat data lagu/musik yang terintegrasi sehingga klaim hak tidak tumpang tindih. Kedua, audit berkala terhadap penghimpunan dan distribusi, agar Royalti Musik benar-benar sampai ke pencipta yang berhak. Ketika dua syarat ini terpenuhi, polemik akan mereda dengan sendirinya karena kepastian dan rasa adilnya lebih mudah dirasakan.
Wajib Tahu:
Royalti Musik bukan pajak dan tidak dibebankan langsung kepada masyarakat. Kewajiban ada pada pelaku usaha/penyelenggara untuk penggunaan komersial, dibayar melalui LMKN. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” bebas royalti karena domain publik.
Kesimpulan
Debat Royalti Musik sebetulnya bermuara pada satu kata: kepastian. Kepastian siapa yang wajib bayar, bagaimana tarif dihitung, dan ke mana uang mengalir. Pemerintah telah menegaskan perlindungan publik dan menyiapkan jalur pembayaran kolektif lewat LMKN. Tugas berikutnya—dan ini penentu—adalah transparansi serta sosialisasi yang konsisten. Jika data dibuka, pelaporan digital berjalan, dan audit diterapkan, Royalti Musik akan menjadi instrumen apresiasi yang sehat: musisi mendapatkan haknya, usaha tetap kompetitif, dan masyarakat menikmati musik tanpa rasa takut “kena tagih”. Sampai ke sana, mari kawal bersama—dengan kepala dingin, data yang rapi, dan kemauan untuk duduk di meja yang sama.
Sumber: Detik