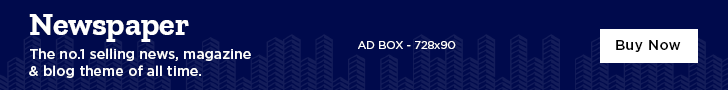Lintas Fokus – (Semiotika) Tragedi Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang meninggal usai dilindas kendaraan taktis Brimob di sekitar Pejompongan, Jakarta Pusat, menyulut duka dan kemarahan publik. Polisi menahan tujuh personel Brimob dan menyiapkan sidang etik seraya membuka peluang proses pidana. Di tengah sorotan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa, meminta maaf “atas nama DPR”, berjanji “mengawal” pengusutan “tuntas dan transparan”, menyerukan “menahan diri”, serta bertakziah ke keluarga Affan sambil menjanjikan bantuan—dari motor untuk ayah Affan hingga dukungan pendidikan bagi saudaranya. Semua fakta ini menjadi pijakan untuk membaca Semiotika ucapannya secara netral namun tegas: apa tujuan tiap kata, dan bagaimana maknanya berubah karena posisi yang ia emban.
Membaca Semiotika “Atas Nama DPR”: Kata yang Menjadi Kuasa
Frasa pembuka “atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI” bukan sekadar sopan-santun. Dalam Semiotika, ini adalah label institusional yang mengubah bunyi empatik menjadi komitmen kelembagaan. Saat kalimat berikutnya berbunyi, “memohon maaf apabila kami sebagai wakil rakyat belum bekerja dengan baik secara sempurna,” maka “maaf” bukan lagi tanda perasaan, melainkan pengakuan performatif akan adanya celah kinerja. Karena pengucapnya adalah Ketua DPR, setiap kata otomatis bertaut dengan perangkat wewenang DPR—fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan—termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Netral-kritis di sini berarti menautkan kata dengan alat: bila ucapan mewakili lembaga, maka publik berhak menagih mekanisme yang sejalan.
Dalam kacamata Semiotika, frasa “atas nama DPR” menaikkan harga makna semua kata setelahnya. Diksi yang terdengar lembut menjadi sarat implikasi: apa rencana rapat, siapa yang dipanggil, kapan tenggatnya, dan bagaimana publik bisa memantau. Kata menjadi kuasa karena disokong oleh palu sidang; di titik ini, perbedaan antara pernyataan pejabat biasa dan Ketua DPR menjadi terang.
‘Maaf’ vs Instrumen Pengawasan: Dari Empati ke Tindakan
“Maaf” adalah tanda reparatif yang lazim dalam komunikasi krisis—menenangkan suhu, mengakui luka sosial, membuka ruang dialog. Namun “maaf” dari Ketua DPR menuntut jalur tindakan: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi terkait dengan Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM; kemungkinan Panja/Pansus bila perlu penyelidikan sistemik; hingga eskalasi menggunakan hak interpelasi atau angket bila rekomendasi DPR diabaikan. Tanpa kerangka yang terukur, Semiotika “maaf” berisiko berhenti pada mikrofon. Publik wajar menagih indikator: jadwal panggilan, daftar isu (SOP pengamanan massa, rantai komando, after-action review), dan publikasi notulensi serta tenggat rekomendasi. Semiotika—sebagai disiplin tanda—mengingatkan kita: kata memperoleh makna dari tindak lanjut yang terdokumentasi.
Di lapangan, Polri telah mengamankan tujuh personel Brimob dan menyiapkan sidang etik, seraya membuka peluang proses pidana. Jika kata kunci Puan adalah “mengawal”, maka DPR perlu menautkan diri pada proses itu secara institusional—misalnya laporan berkala kepada publik tentang progres etik dan pidana, disertai rekomendasi DPR yang bisa diverifikasi. Tanpa itu, Semiotika “maaf” dan Semiotika “mengawal” berjalan di rel yang berbeda.
‘Mengawal’ & ‘Transparan’: Ukurannya Bukan Janji, Melainkan Bukti
Diksi “mengawal” mengandung dua unsur: durasi (tidak instan) dan mekanisme (bukan personal). Karena itu, “mengawal” idealnya bermakna matriks pengawasan:
— Apa yang diawasi (SOP pengamanan, keputusan lapangan, pelatihan ulang).
— Siapa yang dipanggil (Kapolri, Propam, Kompolnas, Komnas HAM).
— Kapan tenggatnya (mingguan/bulanan).
— Bagaimana hasilnya diumumkan (notulensi, rekomendasi, kartu skor publik).
Kata “transparan” pun dapat diukur: apakah identitas pihak yang relevan (sesuai koridor hukum) dijelaskan, apakah update pemeriksaan etik & pidana konsisten, dan apakah lembaga independen dilibatkan. Fakta terbaru tentang pengakuan sopir rantis, alasan kendaraan tetap melaju, dan rencana sidang etik memperlihatkan titik data awal yang bisa diikat DPR ke dalam dashboard pengawasan. Itulah cara membuat Semiotika “transparan” berpindah dari slogan ke arsip tindakan.
Wajib Tahu:
Tiga hak pengawasan DPR—interpelasi, angket, menyatakan pendapat—berasal dari UU MD3. Hak-hak ini dapat dipakai bertahap ketika rekomendasi DPR diabaikan atau ketika pemeriksaan perlu penggalian formal yang berdampak kebijakan.
Bantuan Keluarga vs Perbaikan Sistemik: Dua Jalur yang Tidak Sama
Gestur Puan—takziah, janji motor untuk ayah Affan, serta dukungan pendidikan bagi saudara—bekerja sebagai simbol empati yang nyata. Semiotika membaca gestur itu sebagai tanda kedekatan dan tanggung jawab sosial. Tetapi pada level tata kelola, jalur charity tidak identik dengan remedy sistemik. Remedy sistemik menuntut audit SOP pengamanan, evaluasi komando, after-action review, serta pelatihan ulang—semua ditopang pengawasan DPR yang terdokumentasi. Di sinilah publik mengharapkan koherensi: kata “mengawal” diterjemahkan menjadi seri rapat, rekomendasi bertenggat, dan pelaporan rutin. Ketika hal-hal ini hadir, empati personal dan akuntabilitas negara tidak saling meniadakan; sebaliknya, keduanya saling menguatkan.
Penutup (netral-kritis):
Rangkaian diksi Puan—“atas nama DPR”, “maaf”, “usut tuntas—transparan”, “mengawal”, “menahan diri”—membangun jembatan antara empati dan tata kelola. Namun, karena pengucapnya adalah Ketua DPR, setiap kata semestinya disertai rencana aksi yang bisa diikuti publik: RDP terbuka, Panja/Pansus bila dibutuhkan, kartu skor rekomendasi, serta opsi eskalasi menggunakan hak interpelasi/angket bila rekomendasi macet. Itulah standar wajar agar Semiotika tidak berhenti pada efek kata, melainkan mencapai hasil kebijakan yang terukur dan mencegah tragedi serupa terulang.
Sumber: Detik