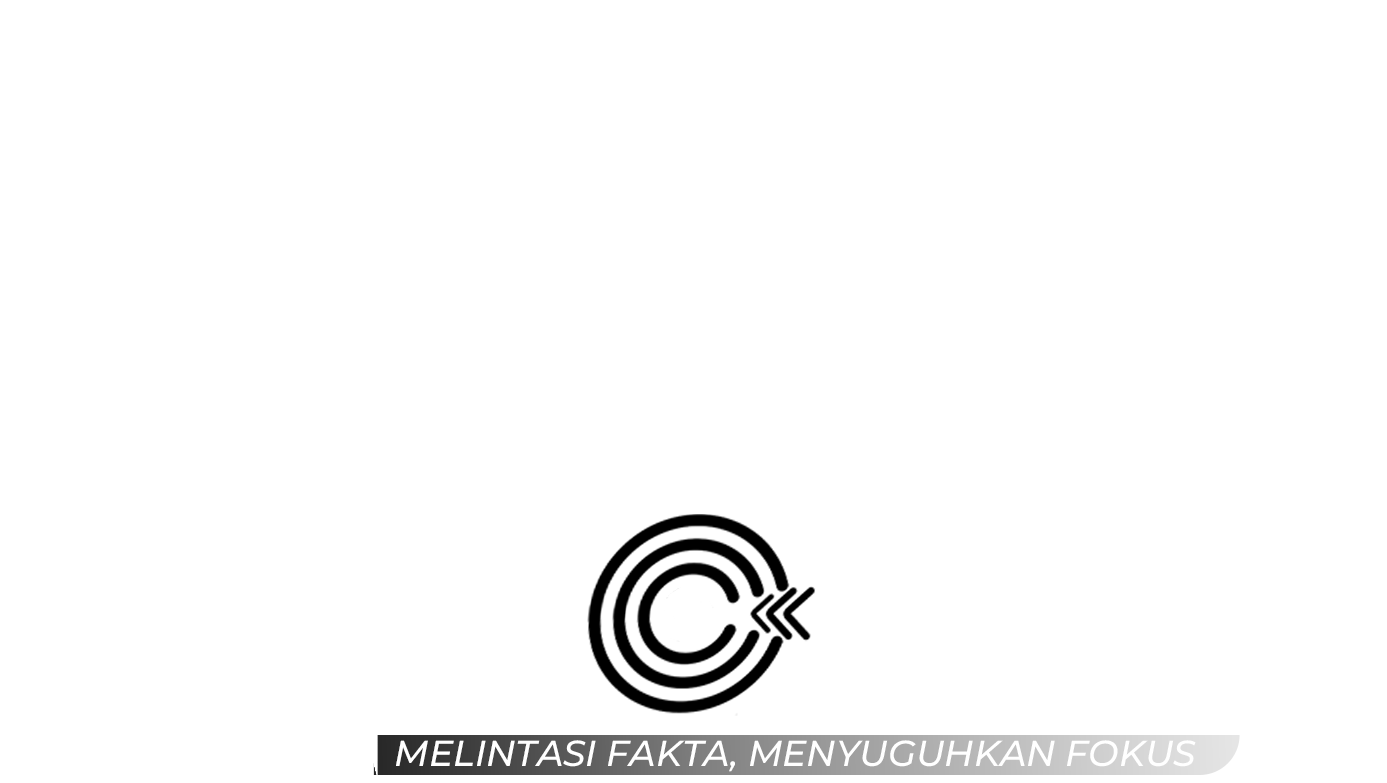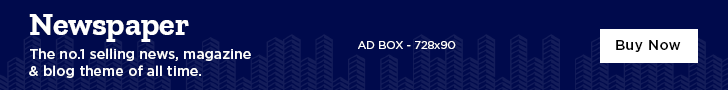Lintas Fokus – Beberapa hari belakangan, dua cuplikan peristiwa menggarisbawahi jurang yang makin terasa antara Wakil Rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Yang pertama adalah video anggota DPR RI berjoget di ruang sidang usai Sidang Tahunan MPR 2025—momen yang, betapapun diklaim terjadi “di akhir acara”, tetap memancing tanya: di tengah keluh rumah tangga soal harga pangan dan biaya sekolah, pantaskah panggung representasi rakyat tampil begitu riang tanpa konteks empatik? Pimpinan DPR Adies Kadir sudah menegaskan itu berlangsung setelah rangkaian inti, tetapi persepsi publik telanjur terbentuk. Kamera warganet menangkap joget, bukan penjelasan; wajar bila emosi mendidih.
Peristiwa kedua lebih menyengat: ucapan “orang tolol sedunia” dari Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) saat menanggapi seruan warganet yang kecewa dan menggaungkan “bubarkan DPR”. Alih-alih menelaah isi kritik, frasa kasar itu terdengar seperti penolakan untuk berdialog. Dalam masyarakat yang makin sadar hak sipil, pilihan kata semacam ini bukan sekadar “salah ucap”; ia sinyal cara sebagian Wakil Rakyat memaknai warga: audiens yang harus dibungkam, bukan mitra yang diajak bicara.
Di luar dua momen tersebut, konteks objektif memperparah luka. BPS mencatat kemiskinan Maret 2025 masih 8,47% atau 23,85 juta jiwa—angka yang memang membaik, tetapi tetap berarti puluhan juta orang hidup di tepi rapuh. Inflasi Juli 2025 pun 2,37% (yoy) dengan 0,30% (mtm), dan media ekonomi merinci pemicunya: beras dan biaya sekolah. Pada dapur keluarga pekerja, frasa “inflasi terjaga” belum tentu terasa melegakan. Maka ketika Wakil Rakyat berjoget atau melontarkan kata bernada merendahkan, wajar bila publik menilai empati kian tumpul.
Saat Kamera Menyala: Joget di Ruang Sidang
Argumen pembelaan bahwa joget terjadi “di penghujung acara” tentu sah. Namun komunikasi publik tidak berhenti pada kronologi; ia juga menyangkut timing, tempat, dan rasa. Ruang sidang adalah simbol mandat. Ketika simbol itu direkam sedang bersuka, sebagian warga—yang baru saja menabung ekstra untuk biaya seragam anak—membaca adegan itu sebagai disonansi empati. Pimpinan DPR telah mengklarifikasi, tetapi video pendek di era platform sosial memang tak pernah datang dengan catatan kaki. Ia menyebar, dipotong, dipelintir, dan diingat. Dalam permainan persepsi, detik joget mengalahkan selembar rilis. Karena itu, Wakil Rakyat perlu disiplin menimbang implikasi visual: bukan sekadar “apa yang terjadi”, tetapi “bagaimana publik membacanya”.
Di titik ini, pelajaran komunikasinya terang: jika ingin merayakan, pindahkan konteks—pilih forum internal, bukan panggung yang meminjam legitimasi rakyat. Jika ingin tetap menutup sidang dengan musik, setidaknya dampingi dengan narasi empatik yang mengakui beban warga hari itu juga. Keterlambatan klarifikasi akan selalu kalah cepat dari laju algoritma.
Kalimat yang Menggores: “Orang Tolol Sedunia”
Bahasa pejabat adalah kebijakan yang diucapkan. Saat seorang legislator menyebut kritik publik sebagai “mental orang tolol sedunia”, pesan yang diterima bukan hanya bantahan; ia terasa sebagai penyangkalan hak bersuara. Demokrasi memang memberi ruang berdebat, tetapi Wakil Rakyat memikul standar lebih tinggi: menjawab argumen dan merangkul emosi, bukan menempelkan label merendahkan pada pengkritik. Jawaban yang ideal bisa berbunyi, “Kami tidak sependapat dengan gagasan pembubaran DPR dan inilah rencana perbaikan, tenggat, serta indikatornya.” Bukan mudah, tetapi justru di situ empati institusional bekerja.
Kasus ini menghadirkan konsekuensi reputasi. Dalam era jejak digital, satu frasa kasar menempel lebih keras ketimbang rilis panjang. Media arus utama merekam kalimat tersebut dan ia berubah menjadi penanda sikap. Upaya merapikan makna setelahnya kerap tak cukup, karena publik memegang “bukti suara” yang berputar tanpa henti di lini masa. Wakil Rakyat perlu ingat: dalam politik kepercayaan, nada seringkali lebih diingat daripada isi.
Mengapa Angka Tak Menenangkan Perut
Boleh jadi pembaca bertanya: bukankah inflasi masih dalam kisaran sasaran dan kemiskinan turun? Benar, di atas kertas. Namun, statistik nasional adalah rata-rata yang menyapu variasi daerah dan komponen pengeluaran rumah tangga. BPS menyebut kemiskinan pedesaan dan perkotaan punya profil berbeda; inflasi Juli 2025 sebesar 2,37% secara tahunan bisa tersembunyi di balik lonjakan beras serta biaya sekolah, dua komponen yang sangat “terasa” di dompet. Karena itu, mengutip angka tanpa menjelaskan kompensasi dan rencana kerja sama saja memoles tembok yang retak dari dalam. Wakil Rakyat yang peka akan langsung menghubungkan data dengan langkah nyata: misalnya, dorongan pengawasan pada bansos tepat sasaran, evaluasi HET beras, atau inisiatif mitigasi biaya pendidikan di tingkat daerah.
Di saat yang sama, publik juga menyorot kebijakan fasilitas pejabat. Ramai kritik soal tunjangan rumah anggota DPR Rp 50 juta per bulan memuncak, lalu ada klarifikasi bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku hingga Oktober 2025 untuk kebutuhan kontrak rumah masa jabatan. Fakta ini penting, tetapi kembali: narasi awal “jangan lihat nilainya, itu biasa” membuat klarifikasi terasa terlambat. Di kacamata warga, kalimat tersebut terkesan defensif, bukannya transparan. Wakil Rakyat semestinya memimpin dengan data komparatif (biaya rumah dinas vs tunjangan), durasi kebijakan, dasar hukumnya, hingga mekanisme audit, agar rasa keadilan publik tidak robek.
Wajib Tahu:
19 Agustus 2025: video joget anggota DPR pada penutup sidang menuai kritik; pimpinan DPR menyebut kejadiannya setelah acara inti. 22 Agustus 2025: frasa “orang tolol sedunia” dilontarkan Ahmad Sahroni untuk menanggapi seruan “bubarkan DPR”. BPS: kemiskinan 8,47% (23,85 juta, Maret 2025) dan inflasi 2,37% yoy (Juli 2025).
Reset Empati Wakil Rakyat: Dari Kata ke Aksi
Jika targetnya memulihkan kepercayaan, empat langkah di bawah ini bisa dijadikan standar minimal—bukan janji, melainkan prosedur yang bisa diaudit publik.
1) Bahasa yang mengakui beban. Berhenti memakai frasa yang menghardik. Ganti dengan kalimat yang mengakui rasa sakit warga sekaligus memaparkan rencana dan tenggat. Setiap ucapan pejabat mesti disertai indikator: tanggal rapat, daftar pemangku kepentingan, dan target penyelesaian.
2) Manajemen momen dan ruang. Hiburan di forum resmi bukan dosa, tetapi timing menentukan makna. Ketika kamera publik selalu menyala, tak ada lagi “momen privat” di ruang sidang. Susun pedoman etika acara agar penutupan sidang tidak membangun persepsi “pesta di atas derita”.
3) Transparansi fasilitas. Untuk isu sensitif seperti tunjangan rumah, tampilkan perhitungan terbuka (biaya dan manfaat) serta batas waktu kebijakan. Jelaskan kenapa kebijakan ada, berapa dampaknya ke APBN, dan bagaimana pengawasannya. Dengan begitu, warga membaca logika, bukan sekadar angka.
4) Kaitkan data dengan intervensi. Jangan hanya mengutip inflasi 2,37% dan kemiskinan 8,47%. Sampaikan aksi korektif yang sedang dan akan dilakukan, dari pengawasan bansos hingga evaluasi komoditas strategis. Ukur kembali efektivitasnya di forum dengar pendapat rutin, dan publikasikan notulensi serta tindak lanjut agar warga melihat gerak, bukan sekadar dengar janji.
Pada akhirnya, empati politik bukan perasaan manis; empati adalah arsitektur komunikasi dan kebijakan. Tanpa itu, joget yang seharusnya merayakan kebersamaan berubah jadi simbol jarak, dan kata yang seharusnya menyejukkan berubah jadi luka. Wakil Rakyat akan kembali dipercaya bila bersedia menahan diri, memilih kata yang tepat, dan yang terpenting: menautkan setiap ucapan dengan kerja nyata yang terukur. Barulah kalimat pejabat terdengar sebagai undangan untuk melangkah bersama—bukan perintah yang membuat rakyat ingin menjauh.