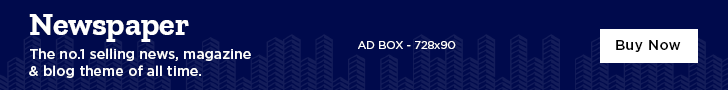Lintas Fokus – Kita sedang memasuki era ketika jawaban “rapi” dan “meyakinkan” bisa keluar dalam hitungan detik. Masalahnya, bukan cuma siswa yang pakai. Mahasiswa pun makin masif memanfaatkan generative AI untuk tugas dan penilaian. Dalam survei HEPI-Kortext 2025 di Inggris, 92% mahasiswa mengaku memakai AI dalam konteks akademik, dan 88% menggunakannya untuk asesmen, melonjak dari tahun sebelumnya.
Di titik ini, sekolah dan kampus menghadapi dilema yang tidak nyaman: kalau semua tugas berbasis tulisan bisa “dibantu”, bagaimana cara memastikan yang dinilai adalah kemampuan siswa, bukan kemampuan prompt? Banyak institusi mencoba perangkat pendeteksi AI, tetapi pendekatan ini sering memicu perdebatan soal akurasi, keadilan, dan bukti. Maka muncul respons yang terdengar seperti kembali ke masa lalu, tapi justru terasa paling logis: Ujian Lisan.
Bukan berarti dunia pendidikan alergi teknologi. UNESCO, misalnya, menekankan pendekatan yang manusiawi, perlindungan privasi data, serta kesiapan kebijakan dan kapasitas manusia ketika menghadapi gelombang GenAI yang berkembang cepat. Namun untuk urusan integritas penilaian, banyak pengajar mulai mengambil jalan yang lebih “tahan banting”: menguji pemahaman secara langsung, real time, dengan pertanyaan lanjutan yang tidak mudah ditebak.
Yang membuat topik ini jadi menarik untuk pembaca Indonesia adalah satu hal: Indonesia sebenarnya sudah akrab dengan ujian berbasis lisan, dari praktik tanya jawab kelas, presentasi, sampai sidang karya tulis. Bedanya, kini Ujian Lisan dibicarakan lagi bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai “pagar” utama untuk mengurangi kecurangan berbasis AI, terutama pada tugas take-home dan asesmen yang tidak diawasi.
Mengapa sekolah dan kampus mulai panik pada kecurangan AI
Gelombang penggunaan AI bukan lagi isu kecil. Data HEPI-Kortext 2025 memberi sinyal kuat bahwa pemakaian AI sudah menjadi kebiasaan mayoritas, dan alasan utamanya sangat manusiawi: menghemat waktu dan meningkatkan kualitas tulisan. Dalam temuan yang sama, salah satu faktor terbesar yang membuat mahasiswa ragu memakai AI adalah takut dituduh curang. Artinya, kebijakan dan desain asesmen sudah menjadi sumber kecemasan baru, bukan sekadar materi kuliah.
Di sisi kampus, ini memunculkan tekanan reputasi. Jika hasil penilaian dianggap mudah “dibeli” oleh AI, maka kualitas lulusan dipertanyakan. Jika kampus terlalu keras melarang, ia akan tertinggal dari realitas dunia kerja yang sudah menjadikan AI sebagai alat bantu standar. Lalu muncul pertanyaan yang lebih tajam: bukan “boleh atau tidak”, melainkan “bagaimana menguji kemampuan yang benar-benar milik siswa”.
Karena itu, banyak otoritas dan lembaga mutu pendidikan mulai mendorong pembaruan asesmen. Quality Assurance Agency (QAA) di Inggris mengumpulkan panduan dan sumber daya untuk menjaga standar akademik di era generative AI, termasuk dorongan untuk meninjau ulang bentuk penilaian di “era ChatGPT”. Sementara di Australia, TEQSA juga menyediakan pusat sumber daya terkait integritas akademik dan reformasi asesmen akibat GenAI, diperbarui pada 10 Desember 2025.
Di tengah tarik menarik itu, Ujian Lisan muncul sebagai solusi yang terdengar sederhana: kalau tulisan bisa “dipoles” AI, maka ajak siswa bicara, minta ia menjelaskan, mempertahankan argumen, dan merespons pertanyaan lanjutan. Cara ini menilai proses berpikir, bukan hanya produk akhir.
Ujian Lisan kembali naik daun, bukan sekadar nostalgia
Tren ini bukan hanya wacana. The Washington Post melaporkan semakin banyak pengajar yang “menghidupkan” ujian oral untuk menguji pembelajaran tanpa keuntungan dari platform AI seperti ChatGPT. Artikel itu juga menyorot bahwa praktik ujian oral memiliki akar sejarah panjang dan kini mengalami “renaissance” karena godaan AI dan perubahan pola asesmen sejak pandemi.
Yang penting dipahami, Ujian Lisan bukan berarti semua ujian harus dilakukan satu per satu di ruangan dosen. Variasinya luas: viva singkat setelah mengumpulkan esai, presentasi dengan tanya jawab mendalam, atau sesi verifikasi untuk memastikan karya tulis benar-benar dipahami penulisnya. Dalam praktik yang lebih modern, ujian lisan juga bisa dilakukan online, asalkan desainnya kuat.
Universitas Edinburgh, misalnya, menjelaskan “live online oral assessment (viva)” sebagai metode yang kembali diminati sejak 2020 karena memberi kontak langsung pengajar dan mahasiswa, serta dinilai sulit untuk curang. Menariknya, viva ini dapat dipakai sebagai asesmen untuk semua mahasiswa, atau sebagai langkah awal ketika dicurigai terjadi pelanggaran integritas akademik, sesuai kebijakan internal mereka.
Dari sudut pandang pembaca Indonesia, pesan yang relevan adalah begini: ketika AI mengubah cara siswa menghasilkan tulisan, dunia pendidikan mulai mengubah cara memeriksa pemahaman. Ujian Lisan menjadi “alat bukti” paling praktis karena siswa tidak hanya diminta menyetor jawaban, tetapi diminta menunjukkan bahwa ia menguasai alasan di balik jawaban.
Desain ujian yang tahan AI: dari viva online sampai studio
Kelebihan Ujian Lisan bukan hanya soal “anti AI”, tetapi soal kualitas pembelajaran. Ujian lisan memaksa siswa mengorganisasi ide, menyusun argumen, dan mempertahankan logika saat dipertanyakan. Di banyak bidang, ini justru lebih dekat dengan realitas kerja: rapat, presentasi, pitching, konsultasi, hingga wawancara.
Namun, agar efektif, ujian oral harus didesain dengan cerdas. Kampus di Eropa juga mulai mengubah format ujian karena AI. Aarhus University, misalnya, menyorot bahwa kecerdasan buatan mendorong sejumlah program studi mengubah bentuk ujian. Pesannya jelas: problemnya bukan pada satu mata kuliah, tetapi pada desain asesmen lintas disiplin.
Di praktiknya, ada beberapa pola yang lebih “tahan AI” dan makin sering dianjurkan pengajar:
Oral verification setelah tugas tertulis
Siswa tetap menulis makalah, tetapi setelah itu ada sesi singkat untuk menguji pemahaman: “Kenapa kamu memilih metode ini?” “Kalau variabelnya berubah, apa dampaknya?” Pertanyaan seperti ini sulit dijawab jika siswa hanya menyalin.Pertanyaan berbasis konteks pribadi atau data kelas
Tugas memakai dataset yang dibagikan mendadak, studi kasus lokal, atau temuan diskusi di kelas. Lalu Ujian Lisan menilai bagaimana siswa menghubungkan data itu dengan teori. Ini mengurangi peluang jawaban generik.Rubrik yang menilai proses berpikir
Fokus pada penjelasan langkah, alasan, dan trade-off, bukan hanya kesimpulan. Dengan begini, AI boleh jadi alat bantu belajar, tetapi tidak bisa menggantikan pemahaman.Pembagian kelas besar ke format “micro-viva”
Untuk kelas besar, modelnya bukan 30 menit per mahasiswa, melainkan 5 sampai 8 menit verifikasi yang sangat terstruktur. Intinya bukan panjangnya, tapi kedalaman pertanyaan.
Wajib Tahu:
Ujian lisan bukan berarti 100% kebal dari akal-akalan. The Washington Post mencatat ada kasus ujian lisan via Zoom yang diduga dicoba “dibantu” AI, tetapi gagal ketika pengajar menuntut jawaban yang mensintesis konsep dan memberi pertanyaan lanjutan.
Kuncinya: pertanyaan lanjutan, cek pemahaman konseptual, dan minta siswa mengaitkan jawaban dengan bukti atau pengalaman belajar yang spesifik. Jika desainnya lemah, ujian lisan bisa berubah jadi formalitas. Jika desainnya kuat, Ujian Lisan menjadi alat yang bukan hanya menekan kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas cara berpikir.
Apa artinya untuk Indonesia: peluang, risiko, dan standar baru
Indonesia tidak mulai dari nol. Kita punya budaya tanya jawab kelas, presentasi, ujian praktik, dan sidang karya tulis. Yang berubah sekarang adalah urgensinya: AI membuat “produk tulisan” semakin murah dan cepat, sehingga penilaian perlu memeriksa “pemilik pemahaman”-nya.
Ada peluang besar jika sekolah dan kampus Indonesia mengadopsi Ujian Lisan secara strategis. Pertama, ia mengangkat kemampuan komunikasi dan argumentasi yang sering jadi kelemahan lulusan ketika masuk dunia kerja. Kedua, ia memaksa pembelajaran lebih bermakna: siswa tidak hanya mengumpulkan, tetapi memahami. Ketiga, ia mengurangi ketergantungan pada alat deteksi AI yang kerap diperdebatkan validitasnya.
Tapi ada risiko yang juga nyata dan harus ditangani sejak desain kebijakan, agar tidak menjadi “boomerang”:
Beban waktu pengajar
Ujian lisan memakan waktu. Solusinya bukan menyerah, melainkan mengubah format menjadi micro-viva, atau memfokuskan ujian oral pada mata pelajaran tertentu yang paling rawan.Bias dan konsistensi penilaian
Penilaian lisan bisa dipengaruhi gaya bicara, kepercayaan diri, atau aksen. Karena itu rubrik harus ketat, pertanyaan harus distandarkan, dan proses moderasi nilai harus jelas.Kesenjangan akses
Jika ujian lisan dilakukan online, kualitas perangkat dan koneksi bisa menjadi faktor penentu. Maka sekolah perlu menyiapkan opsi onsite atau fasilitas yang setara.
Dalam kacamata E-E-A-T, langkah paling kredibel untuk institusi bukan sekadar “mengembalikan ujian lisan”, tetapi membuat sistem yang transparan: aturan penggunaan AI, tujuan asesmen, bentuk verifikasi, dan rubrik. UNESCO menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang melindungi privasi dan membangun kapasitas manusia agar penggunaan GenAI tetap berpusat pada manusia. QAA dan TEQSA juga menempatkan pembaruan asesmen sebagai agenda serius untuk menjaga standar dan integritas akademik.
Kesimpulannya sederhana, tetapi dampaknya besar: ketika AI membuat jawaban semakin mudah dibuat, sekolah dan kampus perlu membuat pemahaman semakin sulit dipalsukan. Dan untuk banyak pengajar, Ujian Lisan adalah cara paling masuk akal untuk menguji “otak yang belajar”, bukan “teks yang rapi”.
Sumber: UNESCO